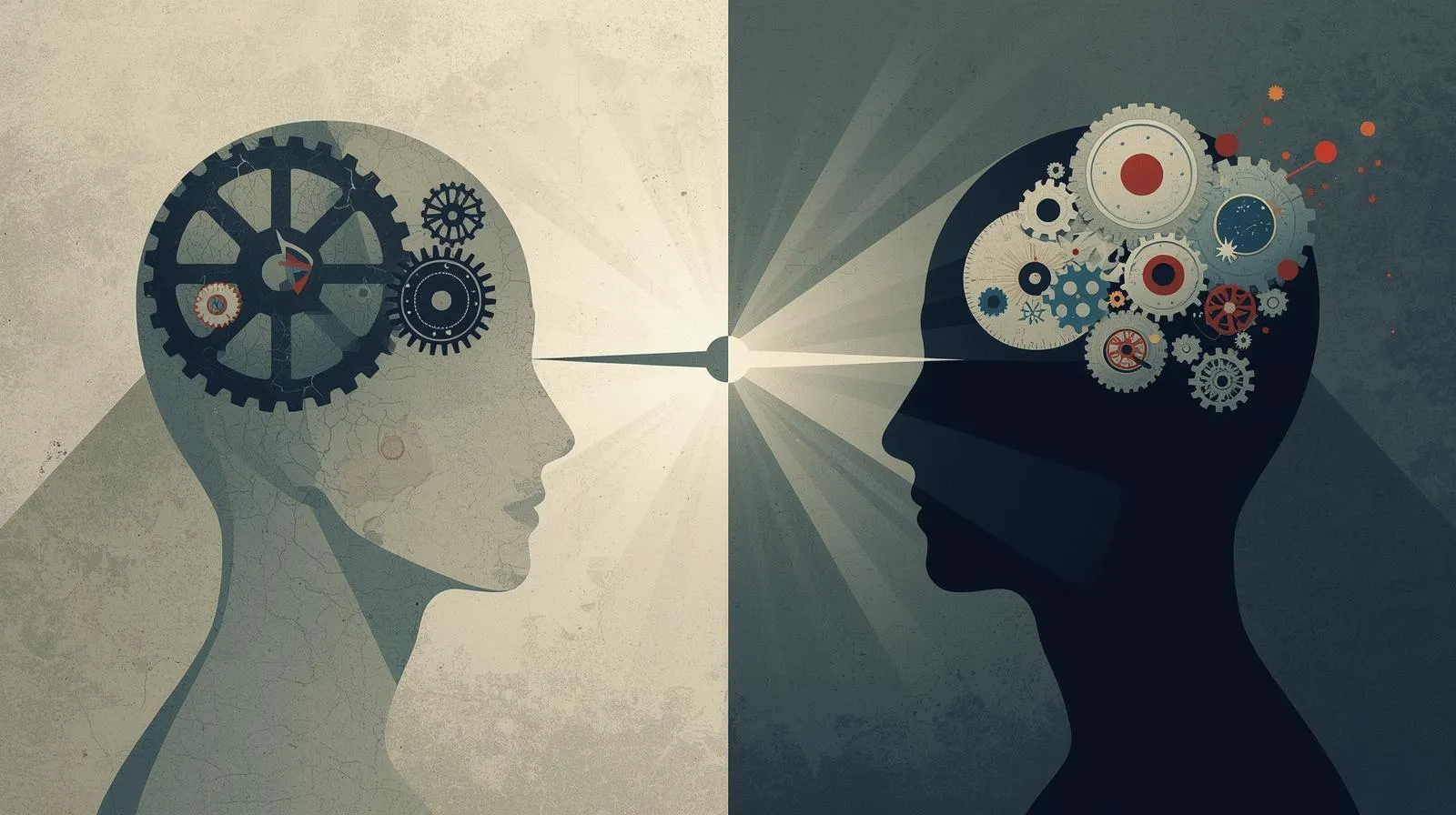Catatan konteks: Artikel ini merangkum dan mengembangkan gagasan utama dari episode Endgame with Gita Wirjawan berjudul “Kecerdasan dan Kebodohan Sama-sama Bisa Dilatih – dr. Ryu Hasan”, yang direkam dalam rangka Endgame Town Hall 2025 dan dibagi ke beberapa segmen seperti empirisme vs abstraksi, cara kerja otak, Gen Z dan parasosial, hingga hubungan kecerdasan, kebahagiaan, dan kekayaan.
Daftar Isi
Otak, Zaman, dan Pertaruhan Kecerdasan
Dalam episode ini, dr. Roslan Yusni Hasan (lebih dikenal sebagai dr. Ryu Hasan), seorang ahli bedah saraf dan neurosains, berdialog dengan Gita Wirjawan tentang tema yang sangat “zaman sekarang”: apakah kecerdasan itu bawaan lahir, kenapa ada orang yang tampak “bodoh permanen”, dan bagaimana budaya digital membentuk cara otak kita bekerja.
Alih-alih memisahkan manusia menjadi “pintar” dan “bodoh” secara statis, dr. Ryu mengajak kita melihat dua-duanya sebagai hasil proses. Otak adalah sistem biologis yang plastis: bisa berubah, menguat, melemah, bahkan “diulang latih” sepanjang hidup.
Dari situ muncul gagasan kunci yang memprovokasi: kecerdasan bisa dilatih, dan kebodohan juga bisa “terpelihara” lewat kebiasaan. Pertanyaannya bukan lagi “saya ini berbakat atau tidak”, melainkan “latihan seperti apa yang saya lakukan pada otak saya setiap hari.”
Empirisme vs Abstraksi: Menyeimbangkan Data dan Imajinasi
Segmen awal episode membahas ketegangan klasik antara empirisme (berpijak pada data dan pengalaman) dan abstraksi (kemampuan merumuskan konsep, teori, dan narasi besar).
Dalam praktiknya:
- Empirisme menjaga kita tetap “menginjak tanah” – keputusan didasarkan pada bukti, bukan perasaan semata.
- Abstraksi memungkinkan kita merancang visi, skenario masa depan, dan kebijakan jangka panjang.
Otak yang hanya berpijak pada data tanpa kemampuan abstraksi akan cenderung reaktif dan pendek napas: jago mengomentari, lemah merancang. Sebaliknya, otak yang terlalu abstrak tanpa disiplin empiris mudah terjebak dalam ide-ide megah yang tidak pernah menyentuh realitas.
Ringkasnya, kecerdasan sehat hidup di tengah-tengah: cukup empiris untuk tidak berilusi, cukup abstrak untuk tidak terjebak rutinitas. Di dunia pendidikan, ini berarti menggabungkan:
- Latihan membaca data, bukti, dan kasus nyata.
- Diskusi konseptual: “Ini artinya apa? Kalau pola ini kita teruskan, apa konsekuensinya?”
Bagi pemimpin organisasi, keseimbangan empiris–abstrak ini menentukan apakah strategi hanya jadi slide cantik, atau benar-benar teruji di lapangan.
Melatih Cara Kerja Otak: Kecerdasan dan Kebodohan Sama-sama “Produk Latihan”
Neurosains modern menunjukkan bahwa otak memiliki kemampuan neuroplastisitas, yaitu kemampuan untuk mengubah struktur dan koneksinya sebagai respons terhadap pengalaman dan latihan yang berulang.
Setiap kali kita mengulang pola pikir atau perilaku tertentu:
- Jalur saraf terkait akan menguat,
- Jalur yang jarang dipakai perlahan melemah,
- Otak mengoptimalkan diri untuk “mode hidup” yang paling sering kita gunakan.
Di titik inilah kalimat “kecerdasan dan kebodohan sama-sama bisa dilatih” menjadi sangat masuk akal. Jika hari-hari kita diisi:
- Scroll pendek, konten dangkal,
- Reaksi emosional instan pada tiap isu,
- Jarang membaca mendalam dan jarang berpikir pelan,
maka otak akan sangat ahli dalam reaksi cepat, tapi miskin analisis dalam. Sebaliknya, membiasakan diri dengan bacaan panjang, diskusi rasional, dan latihan menunda reaksi emosional akan memperkuat jaringan yang menopang konsentrasi dan penalaran.
Praktik melatih kecerdasan (dan berhenti “melatih kebodohan”)
Beberapa kebiasaan konkret yang sejalan dengan temuan neurosains:
- Membaca mendalam secara rutin – bukan hanya judul dan komentar, tetapi artikel panjang, buku, atau laporan yang memaksa otak bertahan di satu topik lebih dari 10 menit.
- Menulis reflektif – menuliskan apa yang dipahami, disetujui, dan ditolak dari suatu gagasan. Menulis memaksa otak menyusun ulang informasi menjadi struktur yang koheren.
- Belajar keterampilan baru – bahasa, musik, pemrograman, desain, dan sebagainya. Riset menunjukkan bahwa belajar skill baru secara konsisten mengubah struktur dan koneksi otak.
- Menjaga tidur, aktivitas fisik, dan nutrisi – faktor biologis dasar ini sangat kuat mempengaruhi kemampuan otak belajar dan beradaptasi.
Tanpa kita sadari, budaya digital bisa menjadikan kita “atlet kebodohan” jika latihan otak sehari-hari didominasi oleh impuls, sensasi, dan kemalasan berpikir. Sebaliknya, disiplin kecil yang konsisten memperkuat kemungkinan otak menjadi “atlet kecerdasan”.
Nihilisme, Spiritualitas, dan Pencarian Makna
Episode ini juga menyentuh ketegangan antara nihilisme (perasaan bahwa hidup tidak punya makna) dan spiritualitas (pencarian makna dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri).
Dari kacamata otak, keduanya bukan sekadar “pandangan hidup”, tetapi lingkungan mental yang kita biarkan menghuni kepala:
- Nihilisme ekstrem bisa membuat otak “hemat energi”: kalau semua tidak bermakna, untuk apa bersusah payah?
- Spiritualitas yang sehat bisa menjadi sumber motivasi, ketekunan, dan ketenangan—selama tidak menutup diri dari data dan realitas.
Tantangan zaman sekarang adalah ketika spiritualitas dipakai sebagai jalan pintas untuk menghindar dari realitas (“biar Tuhan saja yang urus semua”) atau ketika nihilisme dipakai sebagai dalih untuk tidak bertanggung jawab (“toh semuanya tidak berarti”). Kecerdasan dewasa justru muncul ketika kita berani mengerjakan:
- Menerima keterbatasan pengetahuan,
- Namun tetap bertindak berdasarkan bukti terbaik yang tersedia,
- Sambil memelihara nilai dan kompas moral yang manusiawi.
Gen Z dan “Parasocial Relationship Disorder”
Salah satu bagian menarik adalah pembahasan tentang Gen Z dan fenomena yang disebut “parasocial relationship disorder”—ketika seseorang merasa sangat dekat dengan figur publik, idola, atau konten kreator, padahal hubungan itu satu arah dan tidak seimbang.
Otak manusia memang mudah “tertipu” oleh:
- Wajah yang sering muncul di layar,
- Suara yang terdengar akrab,
- Gestur yang terasa hangat dan personal.
Secara neurologis, otak memproses itu mirip dengan relasi nyata, sehingga hormon dan emosi yang muncul pun serupa.
Masalahnya, bila parasosial ini tidak disadari, beberapa hal bisa terjadi:
- Kita menghabiskan energi emosional untuk orang yang bahkan tidak tahu kita ada.
- Ekspektasi tidak realistis terhadap idola: menganggap mereka selalu benar atau suci.
- Kecewa berlebihan saat idola berbuat salah, seolah kita dikhianati secara pribadi.
Kecerdasan di sini bukan sekadar IQ, melainkan literasi emosi dan literasi media:
- Mampu menikmati konten tanpa kehilangan jarak kritis.
- Mampu membedakan kedekatan psikologis dan kedekatan nyata.
- Mampu menyadari kapan konsumsi konten mulai mengganggu hubungan dan tanggung jawab di dunia nyata.
Jika tidak dilatih, kebiasaan hidup di dunia parasosial bisa “melatih kebodohan sosial”—kita tampak update, tetapi miskin pengalaman relasi nyata, miskin empati di lingkungan sekitar.
Mungkinkah Lompatan Kognitif Manusia?
Topik lain yang dibahas adalah apakah manusia masih mungkin mengalami lompatan kognitif besar seperti di masa lalu (revolusi bahasa, tulisan, ilmu pengetahuan), atau kita sudah mentok.
Neurosains memberi jawaban yang cukup optimistis: secara biologis, kapasitas otak manusia belum berubah banyak dalam puluhan ribu tahun, tetapi lingkungan kognitif-nyalah yang berubah—teknologi, pendidikan, dan struktur sosial. Kombinasi neuroplastisitas dan lingkungan yang kaya rangsangan membuat lompatan kognitif selalu mungkin, tapi:
- Ia terjadi di level kolektif, bukan sekadar jenius perorangan.
- Ia membutuhkan budaya yang menghargai belajar, uji bukti, dan koreksi diri.
Pertanyaannya menjadi: apakah kita sedang menciptakan lingkungan yang mendorong lompatan kognitif (melalui pendidikan, riset, diskusi publik yang sehat), atau justru lingkungan yang melatih otak untuk bereaksi, marah, dan fanatik?
Kecerdasan, Kebahagiaan, dan Kekayaan: Hubungan yang Tidak Lurus
Episode ini juga membahas hubungan tiga hal yang sering dikacaukan: kecerdasan, kebahagiaan, dan kekayaan.
Beberapa poin penting:
- Kecerdasan meningkatkan kemampuan kita memecahkan masalah dan mengambil keputusan rasional, tetapi tidak otomatis membuat kita bahagia.
- Kekayaan dapat membeli banyak hal yang mendukung kebahagiaan (kesehatan, keamanan, pendidikan, waktu luang), tetapi tidak menjamin kualitas relasi dan makna hidup.
- Kebahagiaan bergantung pada banyak variabel: rasa aman, kebermaknaan, hubungan sosial, dan tata kelola komunitas—bukan sekadar saldo rekening.
Dalam beberapa wawancara lain, dr. Ryu juga menekankan bahwa “bahagia itu tidak sederhana”: ia merupakan hasil interaksi memori, emosi, asumsi, dan cara komunitas membangun realitas bersama.
Jika kecerdasan hanya dipakai untuk mengejar kekayaan pribadi tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain, ia justru bisa menurunkan kualitas kebahagiaan kolektif. Di sisi lain, kecerdasan yang dipakai untuk meningkatkan kualitas hidup bersama (pendidikan, kesehatan, lingkungan, tata kelola) dapat menaikkan indeks kebahagiaan komunitas secara nyata.
Gembira vs Bahagia, Tertib vs Tenang
Episode ini juga membedakan antara gembira dan bahagia, serta antara tertib dan tenang.
Secara sederhana:
- Gembira / senang adalah emosi sesaat, individual, seringkali terkait aktivitas konkret (makan enak, menang undian, nonton konser).
- Bahagia adalah kondisi yang lebih dalam dan stabil, berkaitan dengan rasa aman, makna, dan hubungan yang sehat dalam komunitas.
Di level otak, kesenangan sesaat sangat terkait dengan pelepasan dopamin yang cepat dan kuat, sementara kebahagiaan jangka panjang lebih terkait keseimbangan sistem emosi dan rasa aman yang berkelanjutan.
Demikian pula:
- Tertib bisa berarti aturan ditegakkan, hukuman tegas, sanksi berjalan.
- Tenang berarti orang merasa aman, dihormati, dan tidak perlu selalu waspada terhadap ancaman.
Sebuah negara atau organisasi bisa tampak tertib tetapi warganya tidak tenang; bisa juga relatif tidak terlalu tertib tetapi warganya justru hangat dan merasa didukung. Kecerdasan kebijakan muncul ketika kita tidak hanya mengejar “ketertiban administratif”, tetapi juga ketenangan psikologis yang membuat otak orang mampu belajar, bekerja, dan berkolaborasi dengan optimal.
Jangan Respons Masalah dengan Masalah
Di segmen akhir, salah satu pesan praktis yang ditekankan adalah: jangan merespons masalah dengan masalah baru.
Ini relevan di banyak level:
- Dalam kebijakan publik: korupsi dibalas dengan regulasi berlapis-lapis yang justru menambah kerumitan.
- Dalam keluarga: anak yang kecanduan gawai direspons dengan marah berlebihan tanpa membangun alternatif aktivitas yang sehat.
- Dalam organisasi: kinerja buruk direspons dengan rapat tambahan dan laporan baru, bukan perbaikan sistem dan dukungan yang nyata.
Secara kognitif, respons seperti itu hanya menambah beban mental tanpa menyentuh akar masalah. Otak manusia punya kapasitas terbatas; jika energi habis untuk memadamkan kebakaran baru, tidak ada ruang untuk belajar dan bertransformasi.
Pendekatan yang lebih cerdas:
- Identifikasi akar penyebab (bukan hanya gejala).
- Rancang intervensi yang mengurangi kompleksitas, bukan menambah.
- Libatkan orang yang terdampak dalam proses solusi (bukan hanya menurunkan instruksi).
Implikasi Praktis bagi Guru, Orang Tua, dan Pemimpin
Bagi dunia pendidikan, pesan “kecerdasan dan kebodohan sama-sama bisa dilatih” sangat menggugah. Artinya:
- Jangan terlalu cepat melabeli siswa sebagai “pintar” atau “bodoh”.
- Fokus pada pola latihan otak yang diberikan: cara mengajar, jenis tugas, cara memberi umpan balik.
- Ciptakan lingkungan yang aman untuk bertanya, mencoba, dan gagal—karena itulah “gym”-nya otak.
Bagi orang tua, ini berarti berhenti hanya memantau nilai rapor dan mulai memperhatikan:
- Apa yang anak konsumsi setiap hari (konten, percakapan, aktivitas).
- Seberapa sering anak diajak berdialog, bukan hanya diperintah.
- Bagaimana keluarga mengelola konflik: dengan dialog rasional atau ledakan emosi.
Bagi pemimpin organisasi dan pemerintahan, pelajaran terbesarnya:
- Kecerdasan kolektif tidak muncul dari satu “jenius” di puncak, tetapi dari budaya yang melatih otak banyak orang untuk berpikir, berkolaborasi, dan berani koreksi diri.
- Digitalisasi tanpa transformasi mindset hanya akan memindahkan kekacauan dari kertas ke layar.
Kesimpulan: Mengambil Alih “Latihan” Otak Kita
Episode Endgame bersama dr. Ryu Hasan ini mengingatkan bahwa otak bukanlah nasib, tetapi proyek jangka panjang. Cara kita hidup setiap hari—apa yang kita baca, bagaimana kita berdialog, bagaimana kita mengelola emosi dan konflik—semuanya adalah “program latihan” untuk kecerdasan atau kebodohan kita sendiri.
Kecerdasan tanpa empati bisa melahirkan sistem yang dingin dan kejam. Kekayaan tanpa kesadaran bisa memperdalam ketimpangan dan kecemasan. Ketenangan tanpa keberanian berpikir kritis bisa menjadikan kita nyaman dalam mediokritas. Di antara semua itu, tugas kita adalah:
- Melatih otak untuk mencari bukti tanpa kehilangan imajinasi,
- Menikmati kesenangan tanpa melupakan kebahagiaan kolektif,
- Memanfaatkan teknologi tanpa menyerahkan hidup pada algoritma.
Jika kecerdasan dan kebodohan sama-sama bisa dilatih, maka setiap hari kita sedang memilih: apakah pola hidup kita hari ini sedang melatih otak menjadi lebih jernih, atau justru semakin kabur? Pilihan itu tidak spektakuler, tetapi diulang ribuan kali. Dan di situlah masa depan kita, pelan-pelan, sedang dibentuk.
Sumber / Referensi
- Video YouTube: dr. Ryu Hasan: Kecerdasan dan Kebodohan Sama-sama Bisa Dilatih | Endgame #242.
- Artikel tentang kebahagiaan dan neurosains yang merangkum gagasan dr. Ryu Hasan: “Bahagia itu (Tidak) Sederhana!”.
- Penjelasan ilmiah tentang neuroplastisitas: “Neuroplasticity – StatPearls – NCBI Bookshelf”.
- Artikel edukatif: “Neuroplasticity: Learning Physically Changes the Brain” – Edutopia.
- Penjelasan populer tentang neuroplastisitas dan kebiasaan: “How Neuroplasticity Works” – Verywell Mind.